Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
- Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
- Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
- Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
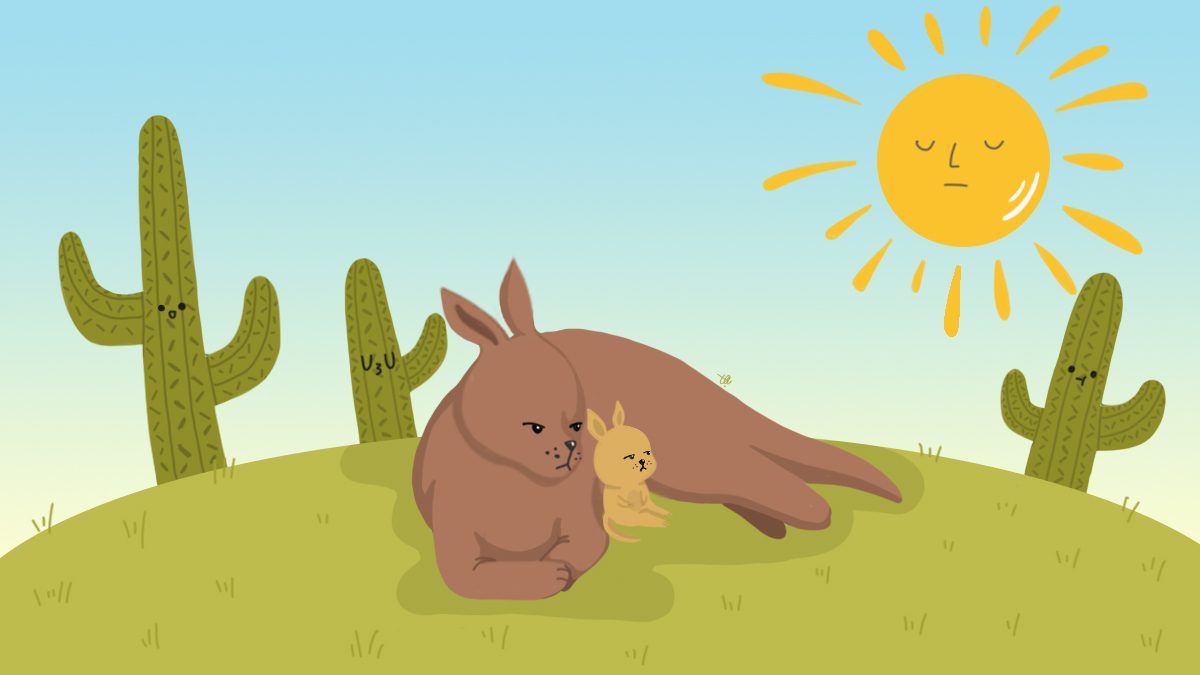
Leave a comment