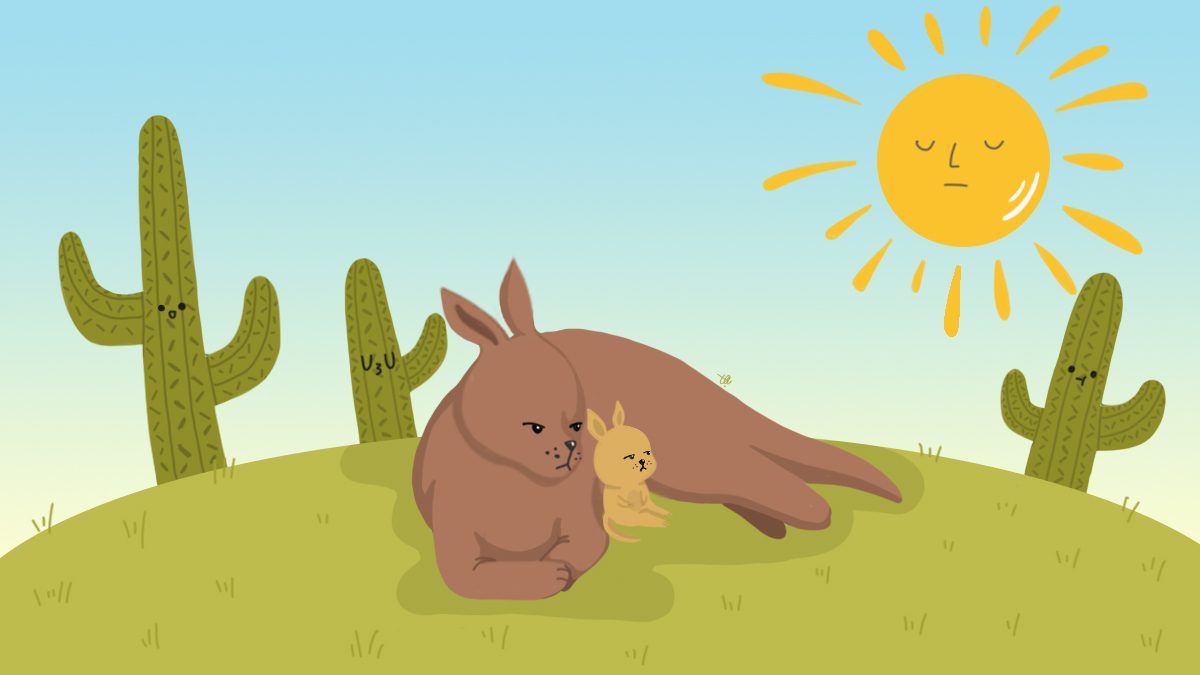Pada tanggal 31 Januari 2019, kasus PT First Anugerah Karya Wisata, atau yang dikenal dengan First Travel, memasuki babak baru. Mahkamah Agung memutuskan aset First Travel yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.[1] Berbagai pihak mengkritik putusan ini karenamenilaiseluruh aset tersebut seharusnya dikembalikan kepada korban, yaitu para calon jemaah First Travel, untuk memulihkan kerugian para korban dalam kasus tersebut.[2] Bahkan hal ini diutarakan pula oleh Kejaksaan sebagai eksekutor[3] dengan menyebutkan bahwa putusan tersebut bermasalah dan sulit untuk dieksekusi. Padahal, Kejaksaan ingin mengembalikan seluruh aset tersebut kepada korban dan Kejaksaan sudah mengajukan hal tersebut dalam tuntutannya.[4] Atas putusan ini, pihak First Travel mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk mengusahakan agar aset First Travel yang diputuskan untuk dirampas negara dapat dikembalikan kepada para calon jemaah.[5]
Sebelumnya, dalam persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok, Jaksa penuntut umum meminta agar aset-aset First Travel yang tercantum sebagai barang bukti nomor 1 sampai 529 dikembalikan kepada para calon jamaah untuk dibagikan secara proporsional dan merata melalui Perkumpulan Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel yang sudah memiliki akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris. Namun, di dalam persidangan, perkumpulan tersebut menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Akhirnya, melalui putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.DPK, Majelis Hakim memutuskan bahwa aset-aset tersebut dirampas untuk negara dengan pertimbangan bahwa barang-barang tersebut bernilai ekonomis dan merupakan hasil kejahatan yang disita dari terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 jo. Pasal 46 KUHAP, barang-barang tersebut harus dirampas untuk negara. Putusan ini kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung pada tingkat banding melalui putusan No. 195/PID/2018/PT.BDG dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui putusan No. 3096 K/Pid.Sus/2018 dengan pertimbangan yang sama.
Dari jabaran di atas, terlihat bahwa terdapat permasalahan mengenai bagaimana seharusnya perlakuan terhadap aset First Travel, apakah seharusnya dikembalikan kepada korban untuk mengembalikan kerugian korban, atau apakah putusan pengadilan sudah tepat dengan memutus aset First Travel dirampas untuk negara. Tulisan ini hadir untuk mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mekanisme pemulihan kerugian korban tindak pidana dan apakah mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kasus First Travel.
(more…)